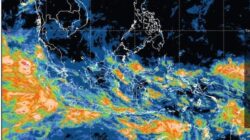Oleh:
Fathoni (Dosen Fakultas Hukum Unila
dalam Peer Group Hukum Administrasi Negara dan Filsafat Kenegaraan)
“Kakofoni (dari bahasa Inggris cacophony, asal Yunani kakos = buruk + phone = suara) secara sederhana berarti campuran suara yang sumbang, keras, tidak harmonis, dan tidak enak didengar. Dalam konteks musik, ini merujuk pada bunyi-bunyian yang saling bertabrakan dan merusak telinga. Lawan katanya adalah Eufoni (suara yang indah/harmonis).”
Awal tahun 2026 mencatat sejarah paling ambisius dalam tata hukum Indonesia. Jika sistem hukum ini adalah sebuah rumah, kita tidak sedang merenovasi rumah, kita sedang merubuhkannya dan membangun ulang dalam semalam. Dengan berlakunya KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) berbarengan dengan KUHAP baru (UU No. 20 Tahun 2025) per Januari ini, kita sedang menyaksikan sebuah “kakofoni” atau kegaduhan hukum yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Jika hukum diibaratkan orkestra, maka hari ini para pemainnya (polisi, jaksa, hakim, advokat) tidak hanya dipaksa memainkan lagu baru, tetapi instrumen musik yang mereka pegang pun mendadak diganti. Tidak ada lagi pemain yang bisa bermain “hafalan”. Semua orang, dari jenderal polisi hingga mahasiswa semester satu, kembali “maaf” menjadi pemula.
Gegar Ganda Aparat: Reset Total
Kekhawatiran lama tentang “ketidaksinkronan” antara KUHP baru dan KUHAP lama kini berubah menjadi kepanikan baru: beban kognitif yang meledak!. Seorang penyidik di Polsek terpencil kini harus memproses kasus dengan dua beban sekaligus: Dia harus mencari pasal sangkaan di KUHP baru yang definisinya berubah, sekaligus harus memprosesnya dengan prosedur beracara di KUHAP baru yang mekanismenya pun masih asing.
Kakofoni ini terdengar nyaring di ruang-ruang penyidikan dan persidangan. Mekanisme baru seperti Jalur Khusus (penyelesaian perkara di luar pengadilan/Keadilan Restoratif yang kini diformalkan dalam KUHAP) atau peran Hakim Pemeriksa Pendahuluan (yang menggantikan praperadilan dengan wewenang lebih luas mengawasi upaya paksa), menuntut perubahan mindset yang radikal.
Aparat yang terbiasa dengan paradigma “tangkap-tahan-hukum” (retributif) kini dipaksa oleh undang-undang untuk berpikir “maafkan-pulihkan-bina” (restoratif). Ini bukan sekadar ganti SOP, ini adalah ganti “iman” hukum. Di lapangan, kebingungan teknis tak terhindarkan: Bagaimana format Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang baru? Bagaimana standar “maaf” dalam restorative justice agar tidak jadi ajang jual-beli pasal?
Universitas yang “Terbakar”
Di menara gading akademis, suasananya tak kalah riuh. Bagi dosen dan mahasiswa hukum, tahun 2026 adalah tahun “pembakaran kitab”. Ribuan buku ajar, jurnal, dan diktat kuliah yang membahas KUHP lama dan KUHAP lama (UU No. 8 Tahun 1981) seketika menjadi artefak sejarah. Validitasnya kadaluwarsa dalam satu malam. Kalau masih mau dibahas, ya dibahas sejarahnya saja.
Dosen tidak bisa lagi mengajar dengan “ auto-pilot “. Mereka harus begadang mempelajari dua UU baru sekaligus agar besok pagi tidak terlihat bodoh di depan mahasiswa yang kritis. Kurikulum Fakultas Hukum di seluruh Indonesia mengalami “gempa bumi”. Mata kuliah Hukum Acara Pidana yang biasanya mapan, kini menjadi mata kuliah yang penuh spekulasi dan perdebatan tafsir.
Mahasiswa hukum angkatan ini adalah angkatan yang paling “sial” sekaligus paling beruntung. Sial karena mereka menjadi kelinci percobaan transisi, beruntung karena mereka adalah saksi hidup revolusi hukum. Mereka belajar hukum yang sedang in the making, bukan hukum yang sudah menjadi fosil.
Masyarakat di Persimpangan Tafsir
Di tengah masyarakat, kakofoni ini muncul dalam bentuk kecemasan akan ketidakpastian. Dengan adanya Living Law (Hukum yang Hidup dalam Masyarakat) yang diakui KUHP dan prosedur baru di KUHAP, batas antara “dosa” dan “pidana”, serta antara “adat” dan “hukum negara” menjadi kabur bagi orang awam.
Apakah penyelesaian adat di kampung sudah cukup menggugurkan tuntutan polisi menurut KUHAP baru? Apakah kritik di medsos bisa langsung ditahan atau harus lewat prosedur mediasi dulu? Minimnya sosialisasi yang masif dan mendetail membuat masyarakat meraba-raba. Hukum yang seharusnya memberikan kepastian (legal certainty), untuk sementara waktu justru memberikan kebingungan (legal confusion).
Menuju Simfoni Baru
Namun, kita harus jujur: kakofoni ini adalah necessary noise (kebisingan yang diperlukan). Kita tidak bisa selamanya berlindung di bawah ketiak hukum kolonial Belanda (Wetboek van Strafrecht dan HIR/Inlandsch Reglement yang menjiwai KUHAP lama).
Kekacauan di tahun-tahun awal ini adalah harga mahal yang harus kita bayar untuk kemandirian hukum. Tantangan kita sekarang adalah mempercepat proses berbelok mencari frekuensi baru (tuning). Mahkamah Agung harus bergerak cepat mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) untuk mengisi celah teknis. Kejaksaan dan Polri harus duduk satu meja menyamakan persepsi agar tidak terjadi gesekan ego sektoral di lapangan. –sepertinya ini sudah mereka lakukan–.
“Kakofoni Hukum Kita” di tahun 2026 ini bukanlah tanda kehancuran, melainkan tanda kehidupan. Seperti bayi yang baru lahir, ia menangis keras dan membuat bingung orang tuanya. Namun tangisan itu adalah bukti bahwa ia bernapas. Hukum nasional kita akhirnya benar-benar “bernapas” dengan paru-parunya sendiri, lepas dari mesin bantu pernapasan kolonial. Sekarang tugas kita adalah merawatnya agar tangisan bingung itu segera berubah menjadi simfoni keadilan yang matang.
Natar, 4 Januari 2026